Nasib jadi pemilik warung kopi nomor wahid se-dusun ya begini. Kena bujuk-rayu tim sukses yang mau menumpangkan spanduk di kedaiku. Kelimpungan karena belum punya pilihan, dan kuatir terhasut kabar burung yang mengepung dari segala penjuru, kuputuskan untuk menemui Pak Guru.
Pucuk dicinta ulam tiba. Esok sore, di tengah jalan, aku berpapasan dengan Pak Guru. Sepertinya, dia baru pulang mengajar. Dia tampak tergesa-gesa.
"Pak Guru, saya mau minta fatwa. Siapa yang harus saya dukung dalam Pildusun kelak?" mohonku, selepas mengucap salam.
"Wah, kamu salah alamat," Pak Guru terperanjat. "Aku ini cuma guru. Mana boleh ngasih fatwa."
"Tapi kan Pak Guru orang berilmu. Suka jadi khatib di masjid."
"Kamu pikir fatwa itu main-main?Fatwa itu pertanggungjawabannya sampai ke langit. Kalau fatwa sudah diucap, pasti sudah lewat proses yang masak, ndak mungkin prematur. Tidak. Aku belum sealim itu. Fatwa itu urusan kyai besar yang sudah qatam membaca hal-hal yang tersirat dan tersurat." Pak Guru bergetar sampai kedua kakinya merapat. "Sudah-sudah, segitu saja ya!"
"Lha, jangan begitu Pak. Ini urusan penting," kecamku atas pengabaiannya."Ya, sudah. Kalau saran saja bagaimana?"
"Nah, kalau itu boleh. Tapi kita bicara di rumah saja ya," jawab Pak Guru tersipu-sipu. Malu-malu, dia menunjuk dengan jempol ke arah rumahnya yang tinggal sepelemparan batu jaraknya.
Aku menggeleng. "Tanggung Pak Guru, bentar lagi mau magrib. Kita tuntaskan di sini saja!"
Muka Pak Guru sontak memerah, nyaris penuh kebencian dan kecemasan.Heran. Apakah dia marah kepadaku?
"Saranku jangan pilih Pak Nyahok!" tetaknya serius.
"Apa ini masalah agama, Pak Guru? Bukankah gak penting warna kucingnya selama kucing itu bisa menangkap tikus? Gak penting agamanya, gak penting bacot comberannya, selama dia bukan pemimpin yang korup."
"Lha, Pak Mangkus dan Pak Manis yang seagama dengan kita itu ndak besar bacot? Apa mereka korup? Belum ada kudengar desas-desus korupsi mereka. Kalau Pak Nyahok itu sudah terang kasusnya. Memangnya kau tidak pernah dengar siaran radio warga? Jangan dibalik begitu ah mikirnya."
"Tapi Pak Nyahok itu petahana Pak. Dia sudah berbuat?" tentangku seraya menyulut rokok.
"Nah, pikiranmu terbalik lagi. Macam rokok itu. Dari mana kau tahu kalau Djisamsu lebih nikmat ketimbang Jarum Coklat?"
"Setelah saya mencoba keduanya, Pak."
"Nah, itu maksudku. Ndak bisa kau menyebut Pak Nyahok itu lebih baik ketimbang Pak Mangkus dan Pak Manis hanya gara-gara dia duluan jadi Kepala Dusun. Itu juga gara-gara dapat warisan durian runtuh saja. Kalau mau adil, coba kau bayangkan seandainya Pak Mangkus atau Pak Manis yang diangkat jadi kepala dusun sewaktu Pakde Jaka terpilih jadi lurah. Kira-kira, dusun kita ini akan lebih baik atau lebih buruk?"
"Hmmm?"
"Yo wis, mikir saja dulu. Lain waktu kita bicara lagi," kata Pak Guru, sudah bersiap-siap angkat kaki.
"Jangan-jangan Pak Guru, langsung saja," papasku.
"Aduh kau ini!" Sekujur tubuh Pak Guru tampak gemetar menanggung perasaan. Dengan geram, dia melantang. "Pertanyaannya begini. Kalau dulu Pak Mangkus atau Pak Manis yang jadi kepala dusun, apa teman-teman SD-mu yang tinggal di bantaran kali itu bakal digusur tanpa ganti rugi? Bakal dipaksa tinggal di kontrakan bertingkat yang bikin mereka semakin miskin?"
"Ndak mungkin, Pak Guru. Pak Mangkus dan Pak Manis itu anti penggusuran."
"Kalau dulu Pak Mangkus atau Pak Manis yang jadi kepala dusun, apa mereka akan menuding ibu-ibu yang minta keadilan sebagai maling dihadapan orang ramai? Apa mereka akan menuduh air mata ibu-ibu yang kena gusur itu sebagai tangis figuran sinetron? Apa mereka akan rela memelaratkan orang-orang miskin supaya dusun kita menjadi lebih cantik?"
"Apalagi itu, Pak!"
"Kalau dulu Pak Mangkus atau Pak Manis yang jadi kepala dusun, apa mereka sebulan sekali mau makan mpek-mpek bareng saudagar anggota naga 9 yang keciduk korupsi itu? Ayo cepat jawab!"
"Terang tidak, Pak. Tapi memangnya saudagar itu sudah keciduk hansip ?"
"Bekas centengnya Pak Nyahok sudah kena. Ada anggota Majelis Desa kita yang juga kena. Kalau Pak Nyahoknya ya ndak tahu aku kapan kenanya." Pak Guru menyeka sebutir keringat yang menggantung di ujung hidung sambil berkeluh-kesah. "Itu urusan hansip. Itu juga kalau hansipnya ndak diajak makan siang sama Pakde Jaka. Nah, sekarang kita lanjut ya? Apa Kyai..."
"Cukup, Pak Guru. Saya sudah paham sekarang," kataku, lalu terperanjat saat menginsyafi wajah Pak Guru yang pucat berkeringat itu. "Pak Guru sakit?"
"Sakit Mbahmu! Sedari tadi aku kebelet, tetapi kau malah maksa ngobrol serius terus."
"Maaf, Pak Guru. Maaf."
Tetapi penyesalanku cuma dipukul angin. Pak Guru sudah membeladag kesetanan menuju rumahnya.
Meulaboh, 5-2-2017














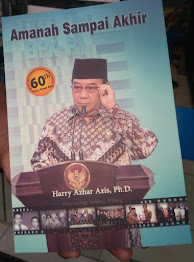
0 komentar:
Posting Komentar