 |
| sumber, twitter Ommah Munir |
Hari itu, seorang pemuda yang baru setahun dapat KTP meradang karena ledakan petasan di luar jendela kamar. Pasalnya, sang ibu yang sedang sakit baru saja terpulas. Ia baru saja mengantarnya pulang dari berobat. Maka, dengan keberanian seorang pemuda, ia keluar dari rumahnya di kawasan Kota Batu. Ia berteriak-teriak, melantangkan tantangan berjibaku. Nahasnya yang membakar petasan tidak seorang diri. Celakanya, karena ditantang oleh pemuda yang lebih kencur, mereka pun kalap. Terjadi pengeroyokan, 1 lawan 30 orang.
Waktu tahu apa yang terjadi,
tindakan pertama si ibu adalah menyuruh adik si pemuda mengambil pentungan.
“Kamu harus tanggungjawab, keluar kamu, berantem
sana!” perintahnya kepada si pemuda.
Sejatinya, sang ibu amat membenci
kekerasan. Tetapi prinsipnya tegas. Harus berani tanggung-jawab atas seganap tindakan
yang telah dilakukan. Si pemuda maklum, maka ia pun keluar rumah lagi. Ia
berjibaku lagi. Dan akhirnya, tentu saja, ia kalah lagi.
Demikian kira-kira satu kejadian
yang membuat Munir bisa dengan asyik bercengkerama dengan teror. Didikan sang
Ibu membuatnya teguh; bahwa setiap kali bertindak, ia sudah harus siap menanggung
risiko. Jadi, kendati motornya pernah
diserempet orang tak dikenal, kerap diancam via SMS, rumah dan kantornya mau
dibom, kantornya diserbu massa, sampai ditodong senapan; Munir terus melangkah di jalan keyakinan yang
telah dipilihnya.
Tetapi mendaulatnya sebagai
seseorang yang urat takutnya sudah putus barangkali berlebihan. Munir pun kerap
didera ketakutan. “Normal, sebagai orang, ya pasti ada takut, nggak ada orang
yang nggak takut, cuma yang coba aku temukan adalah merasionalisasi rasa
takut,” kata Munir.
Akibat hanya membungkukan
punggung pada nilai dan prinsip, Munir harus rela jadi sansak tinju orang
ramai. Ia penah dinisbatkan sebagai aktivis Islam sosialis, tetapi lain waktu
ketika lingkar kekuasaan berganti, ia pun dituduh Yahudi, Kristen sampai
komunis dan antek-antek Amerika. Kontradiktif
dan sulit diterima nalar, tetapi apa mau dikata, Munir sudah terlanjur jadi
objek yang asyik buat dijadikan musuh nomor wahid. Saking masifnya propaganda
intelejen itu, sampai-sampai ada tokoh-tokoh nasional yang keheranan ketika
menemukan Munir bersalat Jumat di mesjid yang sama dengan mereka.
Tetapi, teror yang paling
menyakitkan bagi Munir bukan ancaman hendak dijadikan sosis. Melainkan pada jam
setengah satu siang ada seorang perempuan hamil yang mengadu kepada istrinya
bahwa dirinya telah dihamili Munir. Untungnya, Suciwati yang saat itu sedang
hamil, tidak terpancing. “Saya akan bela kamu supaya Munir bertanggungjawab.
Tunggu sebentar,” pintanya. Tetapi ketika Suciwati kembali dari bersalin,
perempuan itu sudah lenyap.
Munir dan Suciwati memang kompak.
Barangkali soulmate. Saling memahami,
saling kuat-menguatkan. Ketika ada dua aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD)
yang terkena pecahan bom Tanah Tinggi, dan Munir ngotot untuk tidak menyerahkan
mereka kepada tentara. Karena berstatus buron, kedua aktivis itu tidak bisa
dibawa ke dokter. Walhasil, selama tiga hari –deadline yang diberi para
petinggi LBH waktu itu, Suciwati dan beberapa aktivis junior LBH yang sepaham
dengan Munir, merawat mereka dibawah bayang-bayang penangkapan oleh Kopasssus.
Tetapi sebagai pekerja HAM, Munir
juga bukan tanpa cacat. Waktu bergiat di LBH, ia pernah mempermak orang sampai
masuk rumah sakit. Kali lain, ia juga pernah melempar gelas ke muka orang. Ia
tahu bahwa kedua tindakannya itu tidak benar, tetapi emosi terkadang
mengalahkan nalar. Uniknya, ketika Kontras diserbu preman, dan pemuda penggiat
Kontras sudah bertekad tidak ada istilah mengalah, Munir malah berpikir untuk
berdamai saja; agar penyerang itu dilepaskan dari jerat hukum. “Kupikir, biarin
ajalah preman dilepas, musuhku toh yang lain,” katanya.
Segenap cerita ini, saya dapatkan
dari buku Keberanian bersama Munir karangan Meicky Shoreamanis Panggabean.
Sungguh buku yang menarik, karena darinya saya menemukan sosok Munir dari sisi manusia
normal.
Betapa Munir yang besar itu
ternyata baru mengenal kebijakan pengiriman tentara ke Aceh sewaktu ia nyaris
tamat kuliah di jurusan hukum Universitas Brawijaya. Melalui perkawanan dengan
Bambang Sugianto, seorang aktivis jalanan di kampusnya. Perdebatan mereka yang
membawa Munir membaca buku-buku di luar mainstream,
sampai akhirnya menemukan buku Cile,
Revolusi Buruh-nya Arief Budiman. karakternya kian terbentuk setelah
menelisik Nilai Identitas Kader-nya
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menurutnya cerdas radikal dan militan.
Dari proses inilah Munir kemudian menemukan kembali ideologi anti penindasan.
Bagi mereka yang semasa kuliah
gandrung berunjukrasa pasti akan menyebut betapa tidak istimewanya. Faktanya,
banyak di antara mereka yang mengalami proses ini pada akhirnya terjebak pada
ideologi mainstream. Lantas apa yang
membedakan? Abdurahman Wahid menjawab
bahwa dalam berjuang diperlukan penyatuan antara prinsip perjuangan dan tekad
pribadi. Agaknya, Munir memiliki penyatuan itu.
Penyatuan prinsip dan tekad ini
yang membuat Gus Dur hanya bisa termangu ketika Munir berencana menulis
disertasi di negeri Belanda yang akan memaparkan sejumlah orang yang diduganya
menjadi otak pelanggaran HAM berat di Indonesia. Gus Dur paham tak ada gunanya
melarang, bagaimanapun Munir tetap akan melaksanakan niatnya itu. Dan sebagaimana
yang kita ketahui, pada 7 September 2004, Munir tewas diracun dalam
penerbangannya ke Belanda.
Kendati sama-sama berurusan
dengan arsenik, penanganan kasus Munir tidak secepat dan semeriah persidangan
Jessica Wongso. Sampai sekarang, setelah 12 tahun lamanya, aktor intelektual
kasus Munir masih misterius. Konon ia
masih melenggang bebas dan menikmati gelimang kekuasaan.
Kendatipun begitu, saya amat
yakin sang aktor tetap hidup dalam kegelisahan. Karena kepergian Munir tidak
lantas membuat nilai dan prinsip lantas mati. Salah satunya adalah Aksi
Kamisan, di mana sejak 18 Januari 2007, setiap Kamis sore, sekelompok orang
berpayung hitam tegak mematung berjarak sepelemparan batu dari Istana Negara.
Selama satu jam mereka berteriak dalam diam untuk menolak lupa; untuk
mengingatkan pada pemimpin puncak negeri ini bahwa ada pekerjaan rumah yang diwariskan dari presiden ke presiden
yang belum lagi tuntas sampai hari ini.
Hari ini adalah Kamis yang ke-470
kalinya, Aksi Kamisan akan digelar. Tanggal dan bulan yang sama dengan waktu
Munir dilahirkan, 52 tahun silam. Saya sungguh berharap berharap hari ini
Jokowi mau meluangkan waktu untuk menyambangi Aksi Kamisan. Lantas di bawah
naungan payung hitam yang ia pegang sendiri, Jokowi berucap, “Selamat Ulang
Tahun Cak Munir! Hari ini atas nama pemerintah saya berjanji kasus Saudara dan
kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya akan diusut tuntas. Dan mereka yang
bersalah akan dihukum seadil-adilnya.” Lalu Presiden, minimal, memerintahkan
jajarannya untuk berpuasa selfie
sampai urusannya ini beres, dan memberi sanksi kepada mereka yang lelet apalagi
sengaja menghambat. Dan publik akan mengawasi janji itu.
Tetapi, menurut saya mengenang
Munir tidak cukup sebatas itu. Mengenang Munir bukan cuma urusan pemerintah dan
aktivis Aksi Kamisan. Mengenang Munir juga harus dilakukan melalui gerakan
internalisasi HAM dalam sendi-sendiri kehidupan, dan ini menjadi urusan kita
bersama.
Bertekad menjadi Munir, kendati
niscaya, tetapi amat ambisius. Maka, yang paling gampang adalah meneladani
Munir sesuai dengan peran kita masing-masing. Seorang guru yang mengajarkan
anak-anak didiknya tentang toleransi. Seorang tukang ojek yang tidak mengumpat-maki
kepada mereka yang berbeda pandangan. Seorang buzzer pilkada yang tidak main fitnah. Seorang jurnalis yang
menuliskan berita secara benar dan berimbang. Seorang atasan yang tidak
bertindak diskriminatif kepada karyawannya karena soal SARA.
Tentu saja semakin tinggi posisi
dan sumberdaya yang kita miliki akan semakin besar pula prinsip dan tekad Munir
yang bisa kita teladani. Barangkali akan ada pengorbanan, tetapi setidaknya
kita tidak perlu kuatir akan di-Munir-kan. (*)













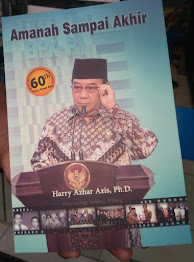
0 komentar:
Posting Komentar