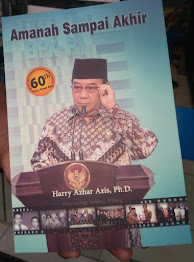Malam ini malam Natal, dan karenanya saya teringat pada Riyanto, anggota Banser NU. Ia sudah berpulang, tetapi namanya selalu hidup di Gereja Eben Haezer Mojokerto.
Saya membayangkan pada malam Natal itu, 24 Desember 2010, Riyanto mengecup punggung tangan sang Ibu, Katinem. Mohon restu untuk bertugas menjaga malam perayaan natal gereja-gereja. Mengendarai vespa merah, Riyanto sampai di Gereja Eben Haezer. Ia bertugas bersama tiga rekannya.
Menjelang tengah malam, seorang jemaat menemukan bungkusan tak bertuan di depan pintu masuk gereja. Di hadapan petugas keamanan, Riyanto membuka bingkisan itu. Sekonyong-konyong terbit percikan api. “Tiarap!,” teriaknya sigap.
Riyanto tergopoh-gopoh keluar. Ia mencampakan bungkusan bom itu ke tong sampah. Nahasnya, meleset. Bukannya menjauh, Riyanto malah kembali memungut bom itu. Ia menamengkan dirinya. Sekali lagi, hendak melemparkan bom itu jauh-jauh.
Tetapi apa mau dikata? Tuhan punya kuasa. Bom itu meledak dalam pelukan sulung dari 7 bersaudara itu. Korban berjatuhan, tetapi khalayak maklum. Tanpa pengorbanan Riyanto jumlah korban akan lebih besar.
Butuh segunung keberanian untuk bertaruh nyawa, dan bertaruh nyawa untuk keselamatan kalangan yang bukan “siapa-siapa” boleh jadi adalah salah satu puncak keberanian. Riyanto sudah melintasi gunung toleransi. Ia bukan sekadar menghargai perbedaan, melainkan mengorbankan diri untuk memperjuangkan harmoni dan sinergi atas perbedaan itu.
Tak pelak, heoisme ini mengingatkan saya pada wejangan K.H. Abdurahman Wahid. “Tidak penting apa pun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.”
Jika kejadian ini ditarik pada situsi-kondisi kekinian, tentu jadi pangling. Dua bulan terakhir ini, bangsa kita dihantam dengan isu Bhineka. Baik media mainstrem maupun sosial media terus menggulirkan sintemen agama dan etnis.
Keteledoran-keteledoran kita merawat toleransi menjadi sasaran empuk untuk objek umpat-hujat. Bangsa ini mendadak menjadi begitu mahir mencari-cari kesalahan, tetapi seolah buta akan prestasi-prestasi toleransi dalam sejarah kita. Framing!Demi menghujat, informasi yang disebar sepotong-sepotong. Dan celakanya, sentimen ini mulai bergerak menjadi aksi baku bully; saling serang.
Bahkan cacing yang diinjak pun akan menggeliat. Permasalahannya, siapa yang jadi cacing? Siapa yang jadi sepatu bot? Jangan-jangan, kita malah menyandang standar ganda; menjadi korban sekaligus pelaku. Atau yang parah: berlagak menjadi korban, tetapi sebenarnya pelaku.
Atau jangan-jangan semua ini sejatinya berada di luar keinginan kita? Jangan-jangan ada operasi intelejen yang dilakukan untuk membuat situasi-kondisi terus memanas? Terus-menerus membayurkan kegentingan amat sangat. Padahal levelnya masih di ambang batas yang bisa kita terima. Level di mana kita bisa bersikap bijak dengan berkata “biar polisi yang mengurus”, bukan malah terseret dalam aksi menyiramkan bensin ke api yang berkobar.
Amatilah baik-baik! Tiga isu yang belakang ini menyibukan ruang publik kita : PKI, Tiongkok dan Agama. Makin celaka, ketiga isu ini ditarik-tarik ke dalam aras politik.
Politik memang asyik, sampai-sampai kita kerap “kehilangan” diri kita sendiri. Dalam membalas kritik kebijakan pemerintah contohnya. Saya sempat menikmati aksi adu argumen di media sosial, termasuk di kolom-kolom kompasiana.
Belakangan kenikmatan ini lenyap akibat kehadiran kaum buzzer pejuang, yang kental aroma afiliasi politiknya, tetapi enggan beradu argumen secara beradab. Dulu, strategi mereka adalah mengalihkan subtansi tulisan ke arah ketiga isu ini; bahwa yang tidak sependapat dengan mereka artinya memberangus bhineka tunggal ika. Belakangan lebih parah, bukan argumentasi yang dibangun, melainkan strategi umpat-hujat.
Hukum aksi-reaksi terjadi. Mereka yang diserang, akhirnya balas menyerang.
Kembali ke laptop, menurut saya, kondisi Indonesia tidak segenting penampakan di media sosial. Mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki nalar yang cukup untuk memfilter segala keriuhan yang menghabiskan energi itu.
Tentu saja masih ada letupan-letupan. Tidak ada gading yang tak retak. Tetapi segenapnya masih bisa diselesaikan secara pancasialis –musyawarah baru kemudian hukum positif. Kendatipun, perlu pula digarisbawahi : jangan pula dipanas-panasi.
Hal ini berpijak pada pengalaman saya menyambangi kawasan –kawasan non muslim, bahkan daerah bekas konflik. Jangankan tindakan, bahkan ucapan yang menyinggung SARA tidak pernah saya terima. Pada banyak tempat saya mendengar kisah-kisah keluarga besar yang para anggotanya memiliki agama yang beraneka, dan undang-mengundang pada perayaan hari besar masing-masing.
Yang paling dekat, ketika anak tetangga saya yang non muslim wafat, tidak ada tetangga-tetangga saya yang memrotes penyelengaraan peribadatan itu. Kendatipun dilakukan di rumah, dan berlangsung sampai malam hari pula. Bahkan kami bergotong-royong untuk menegakan tenda besar untuk menaungi para tamu.
Kalau gagasannya mau diperluas, kita bisa berpijak pada penghormatan kaum Islam pada sidang BPUPKI yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, pada sidang PPKI yang pertama, semua orang sepakat akan redaksional “Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk sila pertama Pancasila. Belakangan, kita juga sepakat bahwa kalangan Tionghoa, baik secara etnis maupun agama Konghucu, menjadi bagian dari keragaman bangsa.
Saya pikir semua itu sudah final. Dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah menyinergikan segenap potensi yang terkandung dalam keragaman itu untuk membantu pemerintah mencapai tujuan Negara Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan malah ribut perihal siapa yang paling paham kebhinekaan.
Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan konsep kepahlawanan baru yang beberapa waktu silam sempat menghinggapi sanubari kita. Semua orang bisa jadi pahlawan! Caranya dengan menebar manfaat sesuai dengan latarbelakang kita masing-masing. Produktif dalam berpikir dan bertindak dalam merawat toleransi dan membangun sinergi antar perbedaan itu. Dan saya amat yakin kalangan seperti ini amat banyak di negeri kita yang sayangnya belum tersentuh media.
Saya pikir ini cara yang paling terjangkau bagi kita untuk meneladani heroisme ala Riyanto. Tidak muluk-muluk, tetapi memiliki efek bola salju.
Akhir kata, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Natal untuk kawan-kawan yang merayakannya. Salam!