”Di sana! Aku lihat
keparat itu!”
Sepersekian detik,
kelima lelaki itu seperti kesetanan. Desing peluru
merobek-robek keheningan hutan, menerabas rerimbunan jeruju. Kawanan monyet terusik dan menjerit-jerit tak karuan. Lolongan anjing kampung
terdengar melengking. Kalong dan burung hantu mengepakan sayapnya, terbang mencabik-cabik kesiur angin senja yang dingin.
Entah karena kekuatan
apa, pada detik yang sama mereka sepakat menahan senjatanya. Waspada mereka
bergerak maju. Tinggal beberapa langkah lagi. Bacin
keringat dingin menusuk hidung. Sesuai rencana, serangan
beruntun itu efektif membuat lelaki itu mencungap-cungap. Jangankan seorang lelaki, bahkan empat
keparat sekalipun bakal sulit bernafas setelah digempur peluru dari empat
penjuru. Namun, semua orang tahu siapa Joko Indo. Seperti kucing
hitam, keparat bengis yang lihai menggunakan senjata api itu memiliki nyawa
sembilan.
Hening menyergap, bahkan
gemerisik angin di pucuk-pucuk pohon terdengar jelas. Mereka menahan nafas.
Semua mata saling mendelik. Kelima lelaki itu dipagut kecemasan, seperti tengah menghampiri lubang kubur mereka sendiri.
Dan nama
besar Joko Indo memang bukan isapan jempol. Dia adalah keparat gila. Mendadak
lelaki itu menyeruak dari balik gerumbulan belukar lengkap dengan sepasang
baretta 45 di tangan. Mereka seolah melihat Izrail telah tercancang di hadapan,
dan sontak menembak. Pun Joko Indo membalas. Jemarinya
cekatan menarik picu, kedua tangannya ligat berputar-putar di udara. Ada tujuh
pistol, tapi terdengar sembilan letusan.
Dua
lelaki tersungkur. Joko Indo bersiap membidik mangsa selanjutnya, ketika ketiga lelaki lainnya
tersadar untuk memprioritaskan keutuhan selembar nyawa yang mereka miliki.
Kesusu mereka berpencar, cari selamat masing-masing. Seorang memasrahkan diri pada pokok
kayu, yang lain memilih rebah di bebatuan tebing, sementara sisanya mencungap-cungap
tiarap di tanah.
Joko Indo menggelagak, lantas bergerak selihai harimau. Dia
cekatan menerobos semak belukar, melompati akar-akar besar yang malang
melintang di tanah. Mudah saja dia berkelit di balik batang pohon besar ketika
ketiga lelaki itu sudah bisa menarik nafas dan balas menembak.
“Bangsat!”
Maki seorang lelaki sambil menatap geram Joko Indo yang
kuyup membeladag ke puncak bukit.
Ketiga
lelaki itu tercancang. Mata mereka menerawang lapisan-lapisan batu yang
tersusun menyerupai tembok menjelang puncak bukit. Arkian, seorang polisi muncul.
Bahunya kanannya koyak ditembus peluru. Darah menderas, dan rasa sakit naik
sampai kepala. Tampangnya pucat, tetapi amarahnya tak sontak surut.
“Kenapa berhenti? Ayo cepat
kejar!” Bentaknya.
Seorang lelaki dengan
jengkel membacokkan pasatimpo[1]-nya
ke batang pohon. ”Target telah melintasi bente[2]?”
”Kalian takut pada
binatang itu?” Hardiknya, teringat berita seekor babi rusa raksasa yang
menyerang para petani di lereng pebukitan Napabale. Konon ketika
dikejar binatang buas itu melarikan diri ke dalam belantara Wakaokili.
”Belantara Wakaokili
dijaga benteno[3].
Mahluk itu seribu kali lebih buas ketimbang babi rusa ganas,” seseorang
menjawab serak.
Logikanya tak berdaulat
menangkap kebenaran mitos. Dengan tatapan jijik dia kembali membentak, ”Joko Indo itu
penjahat besar. Pembunuh, perampok, pemerkosa! Kalian lihat apa yang dia
lakukan kepada Kasat Reskrim Wa Ode? Jangan katakan kalau
kalian mau melepaskannya begitu saja?”
”Maaf, Dan, tapi
yakinlah kalau keparat itu tak bakal keluar hidup-hidup,” ungkap lelaki yang
lain dengan ludahan terakhir sembari berbalik pergi.
Polisi itu menggeram. Menginjak-injak
tempatnya berpijak, sampai nafasnya sesak oleh rasa lelah yang hebat. Dia
meluruskan lengkung punggung, mengatur nafas sambil menengadah. Langit tak tampak
lagi, terhalang rimbunnya kanopi hutan, tapi bisa dia pastikan kalau angkasa
kini dipayungi awan raksasa berwarna pekat. Petir
menggelegar, kilat membelah udara. Sejengkat lagi langkah waktu akan menginjak
malam.
Rasa sakit itu kembali
mendesak sampai ke benaknya. Dia tak mengempit
raincoat, tiada senter, tanpa cadangan makanan dan
kawan sejalan. Kecuali itu, ketika ditinggalkan tadi, Kasat Reskrim Wa Ode tengah sekarat.
Barangkali komandannya akan selamat, tapi bekas peluru bajingan itu akan
menjejak hingga akhir hayat.
Polisi itu menggeleng
lemah. Cukup sudah alasan untuk berbalik pulang.
-()0()-
Joko Indo menapak
lambat di lumpur. Hatinya girang nian. Dugaannya benar. Para
pengejar kelewat takut melintasi bente, apalagi masuk ke perut belantara
Wakaokili.
Hujan turun tak terlalu
lebat karena terhalang kanopi hutan. Namun, dia belum kelewat ahmak untuk
membiarkan tubuhnya kian kuyup. Didakinya pebukitan sampai bertemu ceruk
tebing. Dipetikinya daun-daun trembesi untuk alas duduk. Giginya mengelatuk,
lantaran ranting-ranting basah terlalu pongah untuk dijadikan api unggun. Arkian
dia putuskan untuk mengeliat-geliat dalam ceruk itu, membikin tubuhnya panas
dan berdoa biar hujan cepat reda. Menggagau dalam keremangan cahaya bulan, dia berencana bergerak
menuju perkampungan terdekat.
Tetapi hujan terus
berebut menukik selayak anak-anak panah. Lapar mulai menjeratnya. Dia paksakan
diri untuk tetap bersyukur, sembari menguat-nguatkan hati dengan kalimat: aku haram dalam
keadaan kenyang sebab lapar mempertajam panca indera.
Dari waktu ke waktu dia
terus menggeliat dan menyimak saksama suara-suara rimba. Takut-takut kalau ada
bintang buas memagut atau para pengejarnya itu mendadak nekad, sampai
akhirnya terdengar suara aneh. Joko Indo sontak bertegak
punggung. Tangan kiri menyalakan api mancis. Pistol bersiap di tangan
kanan. Tak sampai tujuh langkah di hadapannya ada rerimbunan semak yang
bergerak-gerak.
“Siapa itu?” Hardiknya, yakin kalau bukan angin
penyebabnya, sebab bahkan lidah api mancisnya tak bergoyang. “Cepat keluar atau aku akan
menembak!”
Tak ada jawaban. Geram
ditembakkannya revolver secara asal ke semak belukar itu. Deru peluru membikin
api mancis padam. Ketika dia menyalakannya kembali, semak belukar itu sudah
berhenti bergerak. Mendadak dari dalam sana melesat keluar sosok mahluk hitam
berkaki empat.
Joko Indo
terkejut, tapi lalu menggelakak. “Keparat! Ternyata hanya seekor musang.”
Joko Indo sudah
kembali meringkuk dan mulai membayangkan kenikmatan seekor ikan bakar. Tetapi nafasnya
mendadak tercekat. Sekonyong-konyongnya sesosok hitam besar melesat, menerkamnya dari
balik semak belukar. Refleks dia menembak. Tetapi sekelebat cakar telah mengebaskan jemarinya
sehingga pistol itu tercampak. Cakar kedua membuatnya terjerembab ke tanah. Selang sekedipan
mata, makhluk itu sudah menindih tubuhnya, bersiap merobek
kerongkonganya.
Kilat menyambar,
membelah udara. Sejenak dunia dibuat benderang. Segenap darah Joko Indo berjingkat ke
benaknya. Makhluk itu bukan babi rusa, apalagi anjing hutan. Mahluk itu
adalah perempuan keriput berkepala nyaris botak dengan sekujur tubuh bersisik ular.
Kuku-kuku tangannya serupa silet, tetapi kakinya seramping kuda
bone.
Joko Indo
memejamkan mata. Pasrah. Mungkin ini nasib seorang penjahat. Tetapi hingga tiga
helaan nafas, dia tak merasakan sakit yang mencabik leher, yang membuatnya
sekarat meregang nyawa. Malahan dia mendengar suara sesungukan.
Dia membuka mata dan
tersadar kalau masih hidup. Tak sampai selemparan batu dari hadapannya,
perempuan itu meringkuk seraya meratap, menjerit histeris.
”Aku tidak bisa! Aku tak
bisa!”
Joko Indo dibunuh
ngeri, tapi keinsyafan membuatnya bersijengkat sebagai ancang-ancang membeladag.
Tetapi perempuan itu seperti memiliki sepasang mata di belakang kepalanya. Dia menoleh, dan
Joko Indo bergidik. Kewarasannya nyaris hilang ketika dalam keremangan cahaya bulan
dilihatnya perempuan itu tersenyum.
”Aku tak akan
berpura-pura kalau tadi hanya sebuah permainan. Ya, aku memang bermaksud
membunuhmu, tapi ternyata aku tidak mampu.”
”Siapa kau? Mengapa kau
mau membunuhku? Apa salahku?”
Kalimatnya mengantung di
udara. Joko Indo merasa pandir. Mengapa pula menanyakan suatu alasan. Sebagai seorang
pembunuh bayaran, perampok, dan pemerkosa, sudah pasti musuh-musuhnya
bertebaran. Mereka semua sangat bernafsu mencabut nyawanya.
”Dengar baik-baik! Aku
bukan seperti apa yang kau pikirkan, bukan setan dari neraka. Aku ini orang
baik, bahkan terlalu baik.”
”Lantas mengapa kau
hendak membunuhku?”
Perempuan itu tak
langsung menjawab. Dalam remang, tangannya bergerak ke arah ceruk batu. Sontak
ranting-ranting basah terbakar.
”Pakaianmu kuyup. Kau
pasti kedinginan.”
”Bagaimana...,” kata Joko Indo gelagapan, mengawasi
lidah api berkobar, ”apa maksud semua ini?”
”Aku adalah puteri kedua
Daeang Arumpone. Dan karena kebaikan hatiku, karena belas kasihku, aku lebih
dicintai rakyat ketimbang kakakku, Daeng Marowa. Namun akibat bisikan Bissu[4]
Sigeri yang mengaku sebagai pembawa kabar Tuhan, Ayah tetap memberikan tahta kerajaan
kepada kakakku.”
Jhony Indo tersurut, teringat
masa bocah ketika sang nenek mendongeng menjelang tidurnya.
”Dengki merasuk jiwaku.
Pada upacara attoriolong[5],
ketika sesajen ditebar, saat gamelan dan kendang berdentangan, dan sewaktu para
bissu menari sembari menusukkan keris, pisau, gergaji ke tubuh mereka, aku pun
bangkit dari singgasana dan menendang mahkota kerajaan sampai jatuh ke bumi,”
serak perempuan itu.
Termangu sudah Joko Indo. Dia sadar
bahwa kalau nanti selamat, tak akan pernah, seumur hidupnya menyebut-nyebut
kejadian ini kepada orang lain. Dia jelas bakal dituding gila.
”Para bissu mengutukku
menjadi mahkluk mengerikan. Ya, mereka paham sekali kelemahanku itu, rasa belas
kasihku. Untuk dapat memusnahkan kutukan ini, aku mesti melakukan suatu dosa
besar. Sebuah pembunuhan...,” lanjut perempuan itu.
”Sebuah pembunuhan?” Joko Indo
mengulang parau.
Perempuan itu cekikikan.
Tawa yang membikin bulu kuduk lelaki itu merinding. Lantas ketika tawa itu
patah, perempuan itu berucap pasrah.
”Jangan takut! Sudah
kukatakan kalau aku ini orang baik. Kesalahan masa silam biarlah menjadi penyesalan.
Mustahil aku mampu menukar kebahagian dengan menyakiti orang lain. Lagi pula
kupikir waktuku sudah sampai.”
Joko Indo
merasakan kalau sekujur tubuhnya dihantam badai hebat. Langit mendadak seakan
berliang. Cahaya putih benderang menyeruak dari dalamnya. Sambil tenggadah, perempuan
itu menghela nafas. Matanya berkerjap-kerjap. Ada kepasrahan teramat sangat
terpancar dari sana.
”Bagaimana nasibmu
nanti?” Serak Joko Indo penasaran.
”Tuhan memiliki cara
tersendiri untuk mengurus orang-orang sepertiku..”
”Aku sungguh menyesal,”
seraknya, mendadak merasa iba. Ya, sontak terbersit keinginan bertaubat.
Pagi-pagi nanti dia akan turun ke kaki bukit dan menyerahkan diri kepada yang berwajib.
Pun masih takut-takut, dia bergerak
mendekat. Tulus disodorkan tangannya. Dia merasakan kalau tangan
perempuan itu lembek dan hangat seperti daging sapi panggang.
”Terimakasih,” katanya dengan
suara tercekat di tenggorokan.
Dengan tampang yang sarat
luka bakar, perempuan itu tersenyum tulus, kendati tetap melontarkan kengerian
yang menyakitkan jantung.
Mendadak senyuman itu
lenyap, dan seperti harimau, perempuan itu menerkam. Joko Indo
terlampau terperanjat untuk menghindar. Mereka bergelantangan di lereng bukit. Dipagut
ketidakpercayaan, dia melihat perempuan itu berhasil berpegangan pada sulur
tumbuhan merambat. Namun, dirinya terus menukik seperti elang tertembak
senapan pemburu. Ternyata ada jurang di tepi sana.
Joko Indo tidak menjerit.
Pasrah. Mungkin ini karma seorang penjahat.
-()0()-
Perempuan itu terjaga di
atas bentangan padang rumput hijau mahaluas. Hidungnya mengendus aroma mawar
dan segar embun yang mengantung di ujung dedaunan. Matahari bersinar teduh,
mengelus tangannya yang mulus. Dia tercekat. Ya, tangannya telah kembali mulus.
Dan rambutnya sekarang memanjang, hitam terurai. Tak ada telaga, apalagi
cermin, tetapi melalui ujung jemarinya, dia sadar kalau parasnya juga telah
kembali cantik.
Dia pun histeris.
Lenyapnya si buruk rupa hanya bermakna satu perkara. Untuk perdana dia menjadi seorang pembunuh. Dia merasa jahat. Amat
jahat.
Tangisnya sedikit
tertahan ketika terdengar keretap langkah kaki. Dia tengadah dan terperanga. Joko Indo tegak
di hadapannya berbalut pakaian putih bersih, wajah bersinar dan senyumnya mengesankan.
”Maafkan aku,” seraknya
sesungukan, ”aku tak bermaksud menyakitimu, ketika itu ada seekor babai rusa
raksasa hendak menerkammu. Aku hanya berusaha menyelamatkanmu, aku...”
Lelaki itu mengulurkan
tangannya. Lembut menyusut butir-butir air yang mengaliri pipinya.
”Tuhan tidak pernah
bermain dadu. Kebaikan hatimu bahkan telah membuat lelaki berlumpur dosa ini diperkenankan mencecap
surga. Sekarang, mana tanganmu? Akan kuantarkan kau menuju istana yang sudah
bertahun-tahun silam disiapkan para malaikat bagi dirimu.”
Kendari, 28 Mei 2008














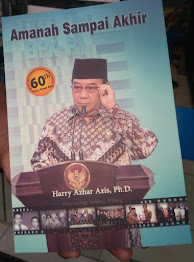
0 komentar:
Posting Komentar