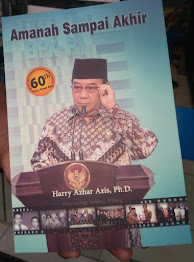Sejak lima tahun silam, Indonesia selalu diguncang isu pengupahan yang lazim dibarengi unjuk rasa besar-besaran. Perlu dicatat, dalam setiap unjuk rasa bukan hanya pengusaha yang pusing.
Setiap unjuk rasa selalu melalui proses panjang dan rumit, yang pasti akan menyedot banyak energi. Mulai dari rapat, konsolidasi, sampai penggalangan dana dan perizinan. Jika boleh memilih, buruh pun ingin bekerja tenang. Tapi, dalam banyak kasus, unjuk rasa dan mogok terbukti lebih jitu sebagai instrumen pemenuhan hak-hak buruh.
Keampuhan unjuk rasa tergambar dari data upah minimum periode 2010-2015 yang naik signifikan. Grafiknya eksponensial. Rata-rata pertumbuhan upah minimum di Indonesia pasca-2010 selalu di atas 15 persen. Bahkan pada 2013, DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Pasuruan naik masing-masing 43,9 persen, 60,9 persen, dan 37,4 persen. Namun, perlu pula dicatat pertumbuhan itu tetap membuat upah minimum Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Thailand, Cina, Filipina, dan Singapura.
Lentingan pertumbuhan upah minimum adalah sesuatu yang wajar. Sebab, setelah sekian lama, pemerintahan Orde Baru mengeksploitasi kaum buruh. Ibarat pegas, semakin kuat penekanan semakin kuat pula tingkat lontarannya.
Namun, harus diakui bahwa lentingan tersebut membuat perusahaan tidak stabil. Pengusaha kesulitan untuk memprediksi besaran upah minimum tahun depan. Kesepakatan yang terjadi antara pengusaha-buruh via Dewan Pengupahan sejatinya adalah kesepakatan sama-sama kalah. Target besaran upah yang dirumuskan buruh dan pengusaha sama-sama tidak tercapai.
Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mencoba menjadi mediator. PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah instrumen untuk mengharmoniskan kepentingan buruh dan pengusaha. Prediksi besaran upah buruh akan memudahkan perusahaan untuk membuat penganggaran tahun depan. Rencana pengembangan perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham bisa lebih dijamin realisasinya.
Sebaliknya, buruh memiliki jaminan bahwa upah minimum akan naik setiap tahun. Upah minimum tahun depan adalah upah minimum berjalan, ditambah upah minimum tahun berjalan dikalikan inflasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat inflasi menjadi simbol pengaman kenaikan barang dan jasa tahun berjalan. Sedangkan, "bagi hasil" atas kinerja perusahaan disimbolkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pada titik ini bisa dipahami iktikad baik pemerintah dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, secara makro meskipun dengan beberapa catatan, PP Pengupahan cukup diterima serikat buruh. Sayangnya, sebelum catatan tersebut sempat dibahas bersama, secara sepihak pemerintah mengetuk pemberlakuannya pada 23 Oktober 2015.
Dari banyak catatan, setidaknya ada tiga catatan penting atas PP Pengupahan. Pertama, upah minimum yang menjadi startup. Pemerintah tidak memberi ruang untuk mengkritisi apakah upah minimum 2015 sudah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal, data Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menunjukkan, pada 2015 terdapat 23 provinsi yang pengupahannya di bawah KHL.
Jika upah minimum yang dijadikan startup sudah di bawah KHL, kemungkinan besar hasil rumusan PP Pengupahan akan kembali di bawah KHL. Ambil contoh KHL Jakarta versi buruh Rp 3,3 juta, tetapi upah minimum 2015 cuma Rp 2,7 juta. Ada kesenjangan Rp 600 ribu atau 22,23 persen. Padahal, UMP Jakarta 2016 cuma naik 11,5 persen karena inflasi 2015 sebesar 6,83 persen dan pertumbuhan ekonomi DKI 4,67 persen.
Kedua, degradasi peran dewan pengupahan dari wadah berunding menjadi tukang hitung rumus. Tidak ada lagi survei lapangan. Cukup mengambil data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS. Permasalahannya, kenaikan harga barang acap lebih tinggi dari tingkat inflasi.
Ambil contoh, data BPS 2014 mencatat harga eceran nasional susu kental kaleng 385 ml dan minyak goreng mengalami kenaikan 13,9 persen dan 8,82 persen dari 2013. Padahal, inflasi tahunan 2014 hanya 7,26 persen.
Rumusan ini akan lebih kacau jika diturunkan ke level kota/kabupaten. Ditemukan rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional pada 11 kota dari 33 kota mengalami kenaikan di atas nilai inflasi 2014. Empat kota kenaikannya sampai dua digit, dengan pemuncak Kota Palembang dan Kota Bengkulu yang mencapai 15,29 persen dan 16,23 persen.
Kondisi ini menggambarkan bahwa penggunaan tingkat inflasi nasional tidak serta-merta bisa mengejar kenaikan harga di level nasional, apalagi lokal. Lantas siapa yang harus menanggung kesenjangan ini? Layakkah menutupnya dengan bagian upah minimum dari pertumbuhan ekonomi? Jika demikian, bukankah artinya kembali buruh yang dikorbankan?
Jika pun hendak dipaksakan, perusahaan hendaknya memberi subsidi upah jika ternyata besaran upah minimum rumusan PP tidak sesuai dengan realitas lapangan. Di sinilah peran dewan pengupahan dibutuhkan, yaitu merekomendasikan besaran subsidi upah. Besarannya berdasarkan pada survei lapangan di masing-masing daerah sebagai pembanding data BPS.
Ketiga, rendahnya kepatuhan pengusaha. ILO Indonesia mencatat 51,7 persen pekerja tetap memperoleh upah di bawah upah terendah yang diwajibkan pada Februari 2015. Ironisnya, kepatuhan ini ternyata memiliki siklus tahunan. Tingkat kepatuhan terendah terjadi pada Februari dan tertinggi pada Agustus.
Ada rentang waktu khusus yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian upah. Butuh beberapa bulan pascadiumumkan, baru para buruh bisa menikmati peningkatan upah. Hal ini tentu merugikan kalangan buruh. Karena itu, dibutuhkan pengawasan dan ketegasan pemerintah untuk memastikan pengusaha merealisasikan kebijakan itu dengan tepat dan cepat.
Intinya, iktikad baik pemerintah yang terkandung dalam PP Pengupahan patut diapresiasi. Sayangnya, pemerintah terlalu tergesa-gesa menerbitkan peraturan itu ketika pokok-pokok substansinya masih perlu dibahas lebih lanjut.
Akibatnya, PP Pengupahan mirip instrumen politik upah murah yang dulu diimplementasikan oleh pemerintahan Orde Baru. PP Pengupahan justru kontradiktif dengan visi trilayak buruh yang digembar-gemborkan Jokowi sewaktu pilpres.
Hendri Teja
Sekjen PB Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo)
sumber republika.co.id