Damang Batu meringkuk di kaki jenjang rumah bentang[1]. Mata ringkihnya
menerawang sisa-sisa kepingan matahari di puncak Bukit Tangkiling. Kelebat
kawanan kelelawar mulai menyesaki angkasa darah. Kesiur angin kemarau pada pucuk-pucuk
trembesi tak berdaulat mengusiknya. Pikirannya terbenam selayak lumpur palung
Sungai Kahayan.
Usianya nyaris tiga perempat abad, tetapi langkah waktu tak pernah berakhir
serupa lembaran potret dalam warna sepia -sesuatu yang indah dan pelan-pelan
memudar. Masa silam adalah catatan harian. Bukan sekadar sesuatu yang
digurat-renungi menjelang tidur, melainkan jaring-jaring ingatan yang
didekapnya ke mana-mana.
Ikhwal itu seperti baru saja dipertontonkan. Badannya segesit enggang dan
jangatnya masih seliat sisik buaya, ketika pada satu malam, saat
tingkap-tingkap atap berderak-derak akibat gempuran hujan, guruh dan kilat,
Ambah[2] memanggilnya ke dalam bilik.
”Sejengkal lagi arwahku akan terbang ke langit. Tak ada harta benda yang
bakal kuwariskan. Sebaliknya, aku hendak mewasiatkan satu amanat yang belum
tentu satu dari seribu lelaki mampu mengembannya.”
Damang Batu tertunduk, ”Anaknda dengar dan patuh.”
Ambah menggebah, ”jangan mencapak! Ini bukan kelakar. Kekhilafan bakal
berujung pada kemalangan jutaan orang.”
Murka Ambah membuat penyakitnya kumat. Begitu hebat deritanya, hingga badan
ringkih itu turut menggelepar-gelepar seiring hempasan badai batuk. Tergesa
Damang Batu mengangsurkan bibir bokor ke ujung mulut Ambah. Lelaki tua itu meludah.
Ludahnya bercampur darah.
”Camkan baik-baik!” Ambah berseru kendati nafasnya masih mencungap-cungap.
”Sepeninggal diriku, mereka akan membeladag menuntut kunci republik. Kau harus
pandai-pandai memilih ahli waris benda bertuah itu. Seseorang yang menghayati
Belom Bahadat[3].”
Damang Batu mencureng. Kecemasan mengumpal-gumpal di dadanya, ”bagaimana
cara Anaknda menemukannya?”
Ambah meneguk segelas air putih, membuka kelopak matanya lambat-lambat,
“Ikutilah kata hatimu. Kata hati seorang lelaki Menteng Ueh Mamut[4].”
Dalam pekan itu pula, Ambah berpulang. Sangkurun, sang dukun kenamaan,
didaulat memimpin upacara pelepasan. Dari delapan penjuru Borneo, ketujuhbelas
kepala suku berkumpul guna memberikan penghormatan terakhir. Arkian, selepas
tari-tarian dipagelarkan, Sangkurun membimbing Damang Batu menombak sapundu[5].
Seorang lelaki tampan dan ramping, tapi jelas lebih jangkung dari segenap
khalayak, meremas bahu Damang Batu, sebelum berganjak ke tengah gelanggang.
“Dalam duka dan suka, dalam derita dan keikhlasan, Damang Gunung telah
menjadi pelindung pilar-pilar bangsa ini. Kendati bermukim di pelosok sungai,
terjerat oleh naungan hijau pebukitan, bahkan ribuan kilometer dari pusat
ibukota negara, sesungguhnya dia adalah negarawan sejati.”
Selepas berpidato, lelaki berpeci itu melompat ke atas perahu jukung.
Sejumlah opsir berkacu yang dikebatkan ke leher seragam khaki, berdegap
mengiringinya. Lekas dayung-dayung ditombakkan ke badan sungai. Rombongan pun
melaju. Menunggangi arus deras menuju muara. Selang beberapa tahun, Damang Batu
baru menginsyafinya. Konon lelaki itu adalah presiden pertama.
“Sudah Magrib, Bue[6],“ seorang bocah bersarung, peci dan baju gunting cina
gedombrong, mendadak menjawil lengannya.
Damang Batu beristigfar. Tersenyum getir dan mengusap kepala Tumbang Hanyu.
Dingin di perutnya belum lenyap. Ikhwal kedatangan mereka, tepat ba’da Isya
nanti, benar-benar menggaduh-ruwet kehidupannya.
“Pergilah dahulu. Insya Allah Bue segera menyusul.“
Tumbang Hanyu menggangguk, mengecup takdzim telapak tangan keriput itu.
Penuh riang, dia berlari-lari kecil untuk bergabung bersama kawanannya yang
menanti di tepi jalan kampung. Sebentar kemudian terdengarlah derai tawa
mereka. Mata Damang Batu pun basah.
Ada yang mengharubiru demi menyaksikan keceriaan itu. Mahaga lewu[7] adalah
darmanya, kewajiban untuk memastikan mereka menjelma anak enggang dan
putra-putri naga sejati. Mereka harus menjadi teratai putih, merekah
suci, tak peduli sebusuk apapun kolam petilasannya.
Sekedipan mata selepas menghela nafas, Damang Batu kembali menerawang ke
ufuk barat. Dirinya pun berbisik, nyaris seperti tercekik.
“Ya Allah, malam ini hamba-Mu ini akan sangat sibuk. Maka bila nanti aku
lupa kepada-Mu, kumohon jangan Kau lupakan aku.“
-()0()-
Gutawa mendengus. Tak pernah terbersit olehnya bisa berada di sini, ribuan
kilometer dari pusat eksotis dan misteri ibukota, dari kepongahan gedung
pencakar langit dan gudang yang menguruk bumi, dari para wakil negara dan para
pelacur yang diusir orang sekampung. Pikirnya, sebagai tokoh spriritual
kenamaan, seharusnya Damang Batu bermukim di perumahan elit, selayak
ustadz-ustadz televisi yang mulutnya berbuih-buih, bukannya di ujung hulu
sungai angker macam begini.
Pandangannya berpendar. Hanya tampak pokok-pokok kayu, habitat kawanan
monyet dan unggas hutan. Sebagai maujud modernisasi –telinganya dijilat raungan
chinsaw, keriuhan belasan heksafagor mengangkat gelondong-gelondong kayu, dan
terengah-engahnya truk dekil sarat muatan yang mendaki pebukitan. Terkadang
perkampungan kumuh khas bantaran sungai mereka lintasi. Selebihnya hanya lindap
lampu getah damar mendominasi.
“Kau yakin ada gunanya kita kemari?” Gutawa menepuk-nepuk perutnya yang
dikocok-kocok speed boat
Kalimat-kalimat Markus meluncur secepat gelombang dan arus, “bukankah Bapak
sudah dengar wejangan Ki Djoko Sedeng? Benda itu bertuah. Presiden pertama
dianugerahi kunci republik, dan berkuasa nyaris seperempat abad. Presiden kedua
merebut paksa, dan 32 tahun memerintah. Presiden ketiga menampik mitos, lalu
tersungkur. Pada masa pemerintahan presiden keempat, konon kunci republik
kembali ke muasalnya. Akibatnya transisi kedaulatan berlangsung cepat.”
”Bukankah pemerintahan presiden keenam sudah masuk periode kedua?”
”Dan saksikanlah bagaimana alam semesta menggugat. Bencana silih-berganti
melanda dari ujung ke ujung.”
Takrif itu menggampar mukanya, membuatnya serupa lelaki terdungu di dunia.
Gutawa menggigit bibir. Tak segala kepongahan terkait ketidakbenaran, terutama
bila Markus yang mengandarkannya.
“Apa kau yakin tua bangka itu bersedia?”
Markus tersenyum licik, “Kali ini kita sepertinya kita harus sedikit
memaksa.”
-()0()-
Rumah bentang bobrok itu serupa nenek renta berhias. Jam emas, dering
blackbery serta lionton dan kalung permata tampak janggal di bawah naungan atap
dari kayu ulin. Hembusan asap cerutu mengabuti ruangan, berpadu tawa-gelak,
debat-tengkar dan kebisuan yang datang dengan satu harapan. Tepat di ambang
pekarangan, barisan lelaki kekar bersiaga. Pada bantalan sungai, pelbagai
speedboat merk ternama tertambat rapi.
Keriuhan mendadak lenyap ketika Damang Batu dan Tumbang Hanyu muncul dari
dalam bilik.
Gutawa lekas menukas, kuatir kalau seorang yang beretorika dasyat bakal
lebih dulu menarik simpati. “Belakangan ini kita terus menyaksikan penghancuran
dan pencabikan anak bangsa. Kesadaran berbangsa musnah, berganti kehidupan
materialistis, hedonis dan individualis. Tragisnya, para penguasa malah sibuk
mengunyah-nguyah perbedaan tak berharga, dijebak pikiran-pikiran dangkal dan
diombangambingkan emosi pandir. Kedatangan kami untuk memperbaiki kondisi itu.
Kami akan berjuang di jalan kebangsaan, jalan yang digariskan para pendiri
bangsa.”
“Ya, benar!“ Khalayak serempak sepakat.
“Aku tak dapat membantu.“ Suara Damang Batu memarau. “Pengemban kunci
republik mesti sosok yang menghayati Belom Bahadat.”
Khalayak tercekat. Mencoba mencerna makna takrif itu.
“Hei, Belom Bahadat itu apa?” Bisik si Politisi kepada pensiunan Kapolri.
.
Lantaran si Pensiunan Kapolri juga tak mengerti, dia nekad menghardik sang
Politisi. “Dasar ahmak! Bagaimana bisa kau jadi politisi, apalagi mau pemimpin
negeri ini?“
Si Politisi naik pitam. “Pelecehan! Saudara mesti mencabut pernyataan tadi.
Saudara juga harus menyatakan permohonan maaf melalui sepuluh media lokal dan
tiga media nasional. Kalau tidak….”
Si Pensiunan Kapolri pantang diancam. Pertengkaran fisik tak terelakkan.
Tak ada yang melerai. Khalayak justru bersorak menyaksikan pergumulan itu.
Beberapa orang malah memanfaatkannya sebagai ajang taruhan.
“Berhenti!” Hardik Gutawa, “Ini rumah keramat bukan ring tinju apalagi
taman kanak-kanak!“
Kendati amarah masih tersuruk di ubun-ubun, kedua petarung itu saling
menarik diri. Para penjudi menggerutu akibat permainan tak tuntas.
Gutawa menyelingai. Dari mulut Markus misteri itu terkuak, “kalau itu yang
Kakek inginkan, maka dengan ikhlas dan tanpa bermaksud pamer, izinkanlah saya
membusungkan dada. Saya adalah pemimpin menghayati Belom Bahadat. Ini
buktinya!“ Gutawa ligat menanggalkan kancing jas. Dari balik kemeja, menguak
t-shirt bergambar wajahnya, sebatang nomor, serta tulisan kapital besar-besar :
PEMIMPIN JUJUR dan BERTANGGUNGJAWAB.
Khalayak tersentak. Hampa serupa botol kosong di dalam kulkas. Tetapi
sedetik kemudian keheningan itu dipecahkan oleh teriakan si Politisi.
“Kalau macam itu, saya pun berhak. Bahkan saya punya empat karakter
sekaligus.“
Hadirin serentak mendongak. Tampang Gutawa sepucat mayat. Tanpa banyak
cakap, si Politisi membentangkan spanduk, sehingga terbacalah tulisan
besar-besar: PEMIMPIN JUJUR, ADIL, CERDAS DAN TERBUKA KEPADA RAKYAT.
Ruangan semakin gaduh. Khalayak beradu membuktikan diri melalui rangkaian
kata-kata pada t-shirt, stiker, pena, sampai papan iklan. Para aktivis
LSM menggelakak seraya memampangkan sertifikat penghargaan anti korupsi.
Kalangan eksekutif mengelu-elukan pelbagai award yang digalas oleh NGO
internasional. Kelompok pengusaha menunjukan laporan keuangan perusahaan yang
telah diaudit akuntan publik.
“Kalau begitu kita semua lulus seleksi,“ tukas seorang aktivis LSM,
“berarti kita semua layak mewarisi kunci republik.”
“Tidak bisa!” Bantah seorang pengusaha. ”Aku lebih berhak. Harta-bendaku
menggunung. Akan kusimpan kunci republik dalam peti kaca berlapis emas,
intan-permata dan bulu merak dalam sebuah museum megah biar rakyat dapat
memahami semangat juangnya.”
“Gagasanku lebih bernas!” Tentang mantan panglima perang. “Kalau aku jadi
pemimpin negeri ini bakal kutetapkan satu hari libur. Nanti kita bikin upacara
megah untuk mengenang marwah kunci republik.“
“Omongkosong! Dengar dulu rencanaku!” Mantan menteri pendidikan tak mau
kalah berargumen. “Data, informasi, semangat dan apalagi itu....., pokoknya
semua ikhwal kunci republik akan diabadikan dalam bentuk buku teks pelajaran.
Bakal kusematkan dalam kurikulum pendidikan sehingga generasi mendatang akan
fasih menghayati hakikat kunci republik.“
Dan kegaduhan masih tak putus-putusnya. Khalayak saling berlomba memaparkan
rencana bila diamanahi kunci republik. Damang Batu makin menunduk, makin
merasakan tusukan-tusukan pedih di dada. Apa yang akan dikatakan leluhurnya
bila tahu kunci republik, simbol integrasi gagasan segenap suku-suku yang
mendiami Nusantara malah diperebutkan para pemimpin berkepala dungu?
“Kakek mau kemana? Urusan kita belum beres!” Gutawa menghadang.
“Urusan kita telah lama selesai. Belom Bahadat adalah ikhwal moral dan
perangai. Pengakuan rakyat adalah yang mendaulat kalian sebagai seorang
pemimpin.”
“Kalem! Saya bisa mendapatkan ribuan KTP sebagai wujud dukungan rakyat,”
komentar seorang walikota
“Apalagi saya, berapa mau tinggal telepon,” sambung seorang anggota DPD
“Masya Allah!” Damang Batu mendesis saking sedihnya. “Allah telah mengunci
hati dan pikiran kalian. Penglihatan dan pendengaran kalian ditutup dari
kebenaran. Bertobatlah sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih.”
Dan Damang Batu membacakan sepotong ayat dari kitab suci. Fatwa kudus yang
dilontarkan pun bergaung. Segenap hadirin termangu. Menelisik mandiri ke dalam
nurani masing-masing. Mendadak mereka merasa berada dalam sebuah masjid
“Tidak bisa!” Gugat Gutawa tak berperasa, “Kami telah memiliki legalitas
Belom Bahadat. Tak bisa dibantah. Kakek mesti memberikan kunci republik kepada
salah seorang dari kami.“
“Jangan-jangan Kakek sudah punya jago sendiri? Belom Bahadat hanya
kamuflase kontrak politik antara Kakek dengan seorang yang juga mencalonkan
diri menuju kursi kepemimpinan negeri ini!” Tuduh si Politisi.
“Kakek harus menyerahkan kunci republik atau kami terpaksa merebutnya!”
Ancam seorang mantan petinggi militer.
“Astaufirullah. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan.”
“Akh, masabodoh dengan para setan!”
Laksana kobaran api, khalayak berkelebat menggeledah seisi rumah. Mereka
membongkar lemari, laci, peti kayu sampai kolong ranjang. Mereka beradu cepat
menemukannya untuk kemudian disurukkan dalam saku jacket, saku jas, tas
kosmetik, kaus kaki atau di mana saja yang barangkali tidak tampak oleh orang
lain.
Dewi fortuna menguntit Gutawa. Dalam peti kayu di ruang tengah ditemukan
kunci emas yang batangnya berukir kalimat tauhid. Tetapi belum sukses dirinya
berkemas, mendadak si Politisi muncul. Tarik-menarik terjadi. Gutawa
terjungkang, Si Politisi menang dan membeladag keluar ruangan. Tetapi belum
sempat menarik nafas gemilang, mendadak dibakar kesumat, pensiunan Kapolri
menghujamkan belati ke dada si politisi.
Kunci republik kembali berpindah tangan. Pensiunan Kapolri sontak diburu
khalayak. Langkah-langkah sigapnya akhirnya patah juga. Dirinya terkepung di
puncak jenjang. Sebentuk kepalan menghantam rahangnya. Membuat tubuhnya
terjungkang. Kunci republik pun terhempas secara parabola. Menggebyur derasnya
arus Sungai Kahayan.
Khalayak tak menyangka bakal sedemikian rupa jadinya. Untuk sekedipan mata
mereka menjadi seragam. Ketika semua orang telah mencoba mengingat-ingat berapa
nomor ponsel penyelam nomor wahid di negeri ini, mendadak kunci republik
mencelat dari dalam sungai, melesat bak anak panah di atas kepala-kepala
mereka.
Khalayak yang tersadar lekas melompat setinggi-tingginya. Gutawa bahkan
nekad menerjang dari atas jenjang rumah. Nahasnya dia justru terpeleset dan
jatuh lintang-pukang.
Kunci republik terus melayang. Pun di belakangnya, khalayak masih terus
mengejar. Tetapi mendadak benda bertuah itu seolah menabrak dinding keras dan
menggeblak lurus ke atas telapak tangan Tumbang Hanyu.
Damang Batu terperanjat, tapi lalu menggelakak, katanya, “sekarang, apa
kalian mau mengakui bocah ini sebagai pemimpin?”
Khalayak seolah magnet yang ditarik ke kutub-kutub bumi. Serempak mereka
meludah ke tanah, lalu melompat ke atas speedboat-nya masing-masing sembari
menceracau.
Palangkaraya, 6 November 2006
[1] Rumah panggung dari kayu khas suku Dayak, yaitu suku mayoritas yang
mendiami Pulau Kalimantan
[2] Bahasa Dayak: Ambah.
[3] Falsafah hidup suku Dayak yaitu perilaku hidup yang menjunjung tinggi
kejujuran,kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum
negara, hukum adat dan hukum alam)
[4] Semboyan orang Dayak yang berarti seseorang yang memiliki kekuatan
gagah berani, serta pantang mundur
[5] Patung dalam upacara pemakaman.
[6] Bahasa Dayak: kakek
[7] Falsafah hidup suku Dayak dalam menjaga kampung halaman.














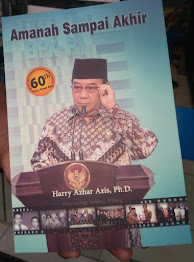
0 komentar:
Posting Komentar