Ngiiiiiiiiiingggg…nguuuuuuuuuunggg...
Jerit speaker
mesjid itu nyaring dan mengerikan, bukti kongkrit kalau gharinnya masih
amatiran. Seketika itu juga Kartini, untuk beberapa saat, merasakan pening di
kepalanya. Meski begitu dia tetap melorot turun dari dipan beralas karpet tipis
yang telah sepuluh tahun belakangan menjadi pembaringannya.
Hati-hati dia
menyalakan lampu minyak agar suaminya tidak terjaga. Listrik rumah kontraknya
sudah dicabut sejak Manto dipecat tanpa pesangon, tepat enam bulan lalu. Untuk
menyambung hidup, mantan buruh pabrik seng itu hanya bisa mengumpulkan
gelas-gelas plastik dari tempat-tempat sampah dan menjualnya kepada juragan
pengumpul.
Kartini
mengangkat lampu minyak itu setinggi ketiak. Dia hendak ke belakang, tetapi
berhenti mendadak ketika cahaya lampu minyak itu, tanpa sengaja, menyinari
kepala suaminya. Lambat-lambat dia bergerak, memastikan kalau matanya belum
lamur.
“Ya, Tuhan.
Betapa cepatnya lelaki itu menua,” desah Kartini sedih. Marto tengah tertidur
nyenyak, mungkin keletihan, sambil mendukung puluhan uban di bagian atas
telinganya. Lekuk yang dalam kini menggaris di sepasang mata suaminya itu.
Dengan
menggotong sekuintal resah di dada, Kartini melilitkan handuk di lehernya untuk
menangkal angin subuh yang acap mencuri kecup di kulitnya. Tangannya menjinjing
ember plastik kecil berisi odol dan sabun ketengan. Dia menyusuri jajaran rumah
tripleks yang berhimpitan -lorong sempit yang menjadi habitat nyaman bagi
tikus, anjing buduk, nyamuk, kecoa dan kumpulan orang-orang terbuang.
Nyaris tak ada
yang memiliki kakus di sana. Panggilan alam itu mesti dilampiaskan pada salah
satu dari dua pintu MCK yang baru-baru ini saja dibangun pemerintah. Kartini
mesti berangkat kerja lebih pagi hari ini, nanti siang ada agenda penting.
Bukannya dia yakin untuk ikut, hanya sekedar berjaga-jaga kalau-kalau perasaan
sebagai seorang kakaknya mendadak memuncak untuk bergerak ke sana.
Ketika Kartini
tiba di sana, orang-orang sudah pada mengantri dengan mata mengantuk dan pipi
bengkak. Sekali-sekali mereka meludah ketika angin subuh membawa bau solokan
mampet atau aroma brankas tinja yang bocor mampir ke lubang hidung. Untuk yang
dikejar waktu, sebenarnya, bisa saja menyeberangi rel kereta api dan jongkok di
atas got. Tak akan ada seorang pun peduli, tapi bahkan di pemukiman kumuh ini
pun kehormatan perempuan tetap di junjung tinggi.
“Tolong
cepetan, Pak! Pagi ini saya ada wawancara kerja di Bekasi,” teriak Marni, yang
berada di urutan hampir buncit, ketika Kusno mendapatkan gilirannya.
Muka Kusno
memerah, seperti baru menenggak miras cap tikus. Lelaki itu memanggil Marni
dengan lambaian tangan, memberikan gilirannya, dan kembali mengantri di urutan
paling belakang.
***
Nguuuuuuuuuunggg… jejesjejes…
Suara itu lagi,
tepat pukul sebelas siang. Mengaung panjang dan menghilang seperti jerit
kerikil yang dijatuhkan ke dalam sumur kering. Seketika, untuk beberapa saat,
dua tukang ojek dan seorang buruh pabrik tekstil, yang tengah menunggu
shift-nya, kesusu menggenggam gelas kopinya masing-masing -kuatir kalau gempa-gempa
kecil itu berbanding lurus dan kewajiban mengganti perabotan pecah belah yang
jatuh ke lantai.
Mardiati hafal
sekali lenguhan ular naga bersisik baja itu, sehafal dia akan kondisi warung
kelontongnya yang sepi sebulan belakangan ini. Tepat di depannya kini sudah
tegak sebuah mini market. Warung kelontongnya dihantam oleh harga murah dan
ruangan sejuk ber-AC. Karena itulah dia nekad membuka warung kopi, peluang
usaha itu ditangkapnya ketika melihat barisan tukang ojek yang jenuh menunggu
para buruh pulang kerja. Dan karena kekurangan modal, maka Mardiati pun
mengantangkan perkakas warungnya itu kepada kemurahan hati seorang tukang
kredit.
“Kopi setengah,
Mbak!” Seorang pelanggan membuyarkan lamunannya.
Ketika tengah
menyeduh racikan gula dan kopi di dalam gelas, Mardiati melihat seorang
perempuan dengan kedua tangan menjinjing dua kantung plastik besar mendekat.
Sesekali, perempuan itu meletakkan bawaannya di tanah, untuk mengusap peluh di
keningnya yang tembaga. Mardiati mendesah, dia juga sudah hafal sekali maksud
kedatangan Kartini ke warungnya ini.
“Tidak,
Kartini. Jangan hari ini,” ketus Mardiati dengan sikap pura-pura sibuk.
“Tolonglah,
Mbak. Si kecil kepingin banget makan sarden kaleng. Nanti saya bayar, kalau
cucian ini sudah dibayar Bu Susi,” rajuk Kartini mengiba.
“Ya, ampun! Apa
kamu tidak bisa berhitung?“ serapah Mardiati, sesaat ingin mengebrak meja untuk
melampiaskan amarahnya. “Hutang kamu itu sudah buanyak. Sepuluh kali upah
cucian macam ini pun belum bisa bikin lunas.”
Muka Kartini
semerah udang rebus. Dia kesusu menumpukan tangan kirinya pada papan penutup
warung kelontong itu. Kepalanya mendadak pusing. Dia tahu kalau dia tengah
keletihan, karena sejak dari jam lima pagi berkeliling kompleks real estate di
seberang pabrik tekstil itu, berharap ada pembantu orang kaya yang kerepotan
lantas memintanya untuk menseterikakan pakaian yang akan dikenakan majikan
mereka ke kantor pagi tadi.
Meski begitu,
Kartini sadar sepenuhnya. Kemiskinan tak mengizinkannya untuk menyerah pada
gugatan biologis. Dia kemudian menguatkan sepasang kakinya, mendorong badan
ringkihnya untuk tegak berdiri. Tapi mendadak ada sepasang tangan yang
menariknya untuk duduk di bangku panjang. Sebentar kemudian, sudah ada segelas
teh manis terhidang di atas meja.
Kartini
tengadah. Mardiati memberikannya tatapan masam.
“Minumlah! Dan
ingat, ini yang terakhir. Benar-benar yang terakhir!” dengus Mardiati sambil
memasukkan dua sarden kaleng ukuran sedang ke dalam salah satu kantung plastik
yang tadi dijinjing Kartini.
***
Ngoooooooooonggg…
Ngoooooooooonggg…
Seperti
lolongan anjing jalanan yang kabarkan kalau malam sudah di pertengahan, seperti
itu pula jerit peluit pergantian shift kerja pabrik tekstil itu. Lolongan yang
panjang, tajam dan memekakkan telinga.
Spontan tiga
tukang ojek itu ligat bergerak. Dua orang bergegas menutup gelasnya dengan
piring tadah, sementara yang seorang, yang cangkirnya sudah kosong, hanya
sempat meneriakkan kalimat yang membuat Mardiati mengurut dada.
“Hutang dulu,
Mbak!”
Dalam hitungan
detik, lalu lintas di depan gerbang pabrik itu langsung kacau balau. Para buruh
seperti rombongan yang menerjunkan diri ke sungai untuk melarikan diri dari
terkaman singa, tetapi mendapatkan diri dikepung gerombolan buaya. Badan bis
yang ngetem sembarangan, angkuh mencegat perjalanan mereka. Selanjutnya,
puluhan tukang ojek berlomba-lomba mengejar mereka, mengepung dari
depan-belakang, kiri dan kanan.
“Minggir!”
teriak seorang satpam, sambil mengacungkan pentungannya ke arah sebuah mikrolet
yang ngetem tepat di depan gerbang. Supir itu tersinggung, kemudian turun dari
mikrolet dan menghujani satpam itu dengan sumpah serapah. Cekcok mulut pun
terjadi. Dan di tengah kekacauan itu, emosi pun acap menabrak ke luar kotak.
“Mampus lu,
satpam brengsek! Makan tuh sok jagoan!” ejek si supir setelah upper cut-nya
telak menghantam rahang lawannya.
Mardiati
bergegas keluar, dia wajib mengetahui detail pertikaian tersebut. Gosip renyah
adalah penikmat rasa minum kopi, salah satu layanan istimewa di warungnya.
Tetapi baru tiga tapak dia melangkah, mendadak sebilah tangan yang kukuh
mencengkramnya.
“Jangan usil!
Sudah, urus saja urusanmu sendiri,“ bentak Markonah, perempuan gemuk dengan
sepasang pipi penuh liang bekas cacar. Tangan kanannya kemudian langsung
tenggadah, “mana uang sewa warungmu?”
"Tak
bisakah ditunda, Bu? Warung saya sedang sepi-sepinya," jawab Mardiati
dengan mimik mengiba, “saya janji awal bulan nanti pasti saya lunasi semuanya.”
Markonah
mendengus jengkel, "itu yang kau katakan tepat enam bulan yang lalu.
Jangan suka membohongi orang tua. Nanti kualat, baru tahu rasa!”
“Tapi, Bu…”
“Ini hari aku
enggak mau denger kata ‘tapi’. Ngerrrrrrrrti?”
Mardiati pucat
pasi. Dia sadar kalau keinginan Markonah sudah tak mungkin ditawar-tawar lagi.
Dengan mata sembab, seperti kucing kelaparan, dia memutari meja dan membuka
laci kasnya.
“Tolong Dji Sam
Soe setengah, Bu!”
Kemunculan
mendadak seorang pemuda gondrong dengan celana jeans, sepatu kets, dan tas
sandang di bahunya, membuat Mardiati mendadak histeris. Pemuda itu kebingungan,
tetapi karena tangis Mardiati tidak memperlihatkan tanda-tanda akan segera
berakhir, dia memutuskan untuk mencari warung yang lain.
“Sudah berapa
tahun?” bisik Markonah dengan nafas resah, seolah-olah mencoba meyakinkan
dirinya sendiri.
“Sudah empat
kali ganti presiden, Bu. Tapi nasib puteraku itu belum juga jelas…,” jerit
Mardiati sesungukan.
“Putera kita,”
Markonah berbisik sendu, memotong. “Elang, anakku, juga kemungkinan besar jadi
korban penculikan itu,” ucapan Markonah berhenti. Nafasnya mendadak sesak, dan
matanya pun mulai berkaca, “ Akh -aku masih ingat sekali sore itu. Dia mencium
tanganku. Katanya mau pergi berjuang membela negara. Sejak sore itu, dia tidak
pernah kembali.”
“Salah – salah!
Mereka bertiga adik saya juga. Mbak dan Ibu jangan lupakan Abduh!”
Mardiati dan
Markonah, Ibu para putera yang hilang, menoleh serempak ke arah sumber suara.
Kartini tampak tegak di sana, lengkap dengan daster lusuh, wajah pucat dan
bacin keringat -penampilan yang benar-benar khas perempuan miskin. Tapi mata
itu, di dalam sepasang mata itu, keduanya serasa dapat melihat ledakan-ledakan
granat.
Markonah
menatap perempuan itu, dengan matanya, dengan hatinya, dengan seluruh
perasaannya. Dia kemudian melambaikan tangannya, mengundang Kartini untuk
menyempurnakan segitiga kesedihan itu. Kemudian ketiga perempuan itu pun saling
berdekapan, terisak bersama atas nama kegetiran hidup.
Mendadak kepala
Mardiati terangkat. Matanya, meski sembab, kini kembali meledak-ledak.
“Sebentar,
Mbakyu-Ibu. Rasanya kok tak enak menyerah begitu saja pada kezaliman ini.”
“Kau benar,
Tini. Kau benar,” jawab Mardiati, masih kesulitan meredam isak tangisnya.
Markonah
membisu. Perempuan gemuk itu kemudian menyeka air matanya dengan saputangan
dekil. Dia menarik nafas panjang, sebelum memutuskan untuk berlari ke arah
jalan raya.
***
Ngeeeeeeeeeeenggg…
uhhhuk…uhhhuk.
Mesin bajaj itu
batuk-batuk, menyadarkan ketiga perempuan itu kalau mereka pasti terlambat.
Ancaman dari serudukan bis-bis Patas AC -para sopir gila yang seakan memiliki
kepuasan sendiri dengan menteror bajaj, atau becak kalau ada- serupa banteng
liar di tengah jerit klakson dan bising mesin, membuat mereka bersyukur kalau
masih bisa mendengar pidato penutupan.
Ketika mereka
tiba di Taman Suropati, arak-arakan protes massa sudah bergerak menuju Bundaran
HI. Bajaj itu berhasil mencegat rombongan di Tugu Tani. Ketiga perempuan itu
langsung bergabung, meski sempat kebingungan karena ini adalah yang pertama.
Mereka menumpahkan kesedihan, kemarahan, harapan, dan rasa pasrah melalui
slogan-slogan yang diteriakkan dengan jerit histeris.
“Kembalikan
putera kami! Kembalikan adik kami! Kembalikan saudara kami!”
Arak-arakan
sampai ke tempat tujuan. Seorang perempuan muda dengan ikat kepala merah darah
beringsut ke tepi kolam, sehingga dapat lebih jelas dilihat massa. Dia
berteriak, melalui megaphone, memanggil pengarah unjuk rasa -Suminten, SH.
Selusin
perempuan kemudian membelah kerumunan, di tengah-tengahnya Suminten, SH
bergerak lambat-lambat menuju panggung. Kartini tercenung, tidak menyangka
kalau malaikatnya itu adalah perempuan berpostur pendek gemuk dengan balutan
rok dan blazer serta rambut disanggul mewah -khas penampilan ibu-ibu PKK yang
acap dia lihat muncul di teve tetangga.
Sambil
melangkah, Suminten, SH tersenyum lebar dan melambaikan tangannya kepada
orang-orang. Pergelangan tangan perempuan itu pun tersingkap. Mardiati
terkesima, yakin sekali kalau tangan itu tidak sekedar dipenuhi perhiasan
imitasi, melainkan rangkaian gelang emas dan dua cincin berlian, yang
memendarkan sinar matahari ke segala penjuru.
Di samping
Mardiati dan Kartini, ada Markonah yang tengah giat-giatnya meninju langit.
Anehnya tangan Markonah itu tidak terkepal, malahan seakan tidak ada kebencian
di sana -yang ada hanyalah rasa pasrah dan sejumput tanya :“Benarkah perempuan
di atas panggung itu juga kehilangan seorang putera?”
Padang 1 Oktober 2006














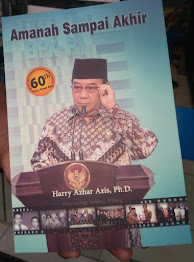
0 komentar:
Posting Komentar